
Peran Strategis Pendidikan Agama Kristen sebagai Penggerak Budaya Digital yang Berkeadilan, Damai, dan Membangun
Oleh: Dr. Djoys Anneke Rantung, S.Th., M.Th., D.Th.
Abstrak
Perkembangan teknologi digital telah membawa berbagai dampak positif dalam kehidupan manusia modern, terutama dalam akses informasi dan komunikasi. Namun, dibalik kemajuan tersebut, muncul ancaman serius berupa kekerasan dalam konten digital yang tersebar luas melalui berbagai platform media. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana kekerasan konten digital memengaruhi psikologi individu, struktur sosial, dan masa depan generasi muda. Pendidikan Agama Kristen memiliki peran strategis sebagai fondasi iman untuk membentuk karakter, moral dan etika bangsa dengan budaya digital yang berkeadilan, damai dan membangun. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dan kajian Pustaka multidisipliner, tulisan ini menyoroti urgensi literasi digital, regulasi etis, serta peran pendidikan agama Kristen dalam merespons ancaman ini secara holistik. Artikel ini menyimpulkan bahwa kekerasan konten digital merupakan potensi malapetaka masa depan apabila tidak ditanggapi dengan bijak dan strategis.
Kata kunci: kekerasan digital, media sosial, generasi muda, literasi digital, etika teknologi.
Pendahuluan
Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi informasi, dunia digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Era digital yang kian berkembang, masyarakat global menikmati kemudahan dalam mengakses dan membagikan informasi. Kemajuan teknologi ini membawa transformasi besar dalam pola komunikasi, pendidikan, dan hiburan. Media sosial, platform video, game daring, hingga situs berita, kini menjadi ruang terbuka bagi berbagai bentuk ekspresi dan informasi. Namun, di balik pesona dunia digital, tersembunyi persoalan mendalam, suatu realitas yang mengkhawatirkan yakni menjamurnya konten digital yang sarat kekerasan serta meningkatnya kekerasan dalam konten digital.
Paparan konten digital seperti ini tidak lagi terbatas pada kelompok dewasa, tetapi telah menjangkau anak-anak dan remaja yang mengakses media digital tanpa kontrol. Akibatnya, terjadi peningkatan kasus psikologis seperti kecemasan, desentitisasi terhadap kekerasan, dan menurunnya empati sosial. Pertanyaannya, jika tren ini terus dibiarkan, apakah kekerasan konten digital akan menjadi malapetaka bagi masa depan generasi?
Fenomena kekerasan konten digital ini meliputi penyebaran video kekerasan, cyberbullying, ujaran kebencian, hingga konten game yang menjadikan kekerasan sebagai bentuk hiburan atau glorifikasi perilaku brutal dalam game atau media hiburan, semuanya dengan mudah diakses, bahkan oleh anak-anak dan remaja. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: Apakah kekerasan dalam konten digital hanyalah bagian dari ekspresi kebebasan berekspresi, ataukan merupakan ancaman nyata yang menjadi malapetaka bagi masa depan? Di tengah minimnya literasi digital dan lemahnya filter etis dalam konsumsi media, generasi muda sangat rentan menjadi korban maupun pelaku kekerasan yang didorong oleh paparan konten tersebut.
Kekerasan konten digital bukan hanya berdampak pada kesehatan mental individu, tetapi juga dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Normalisasi kekerasan dalam ruang digital berpotensi melahirkan masyarakat yang desenitisasi terhadap penderitaan sesama, menurunnya empati, serta meningkatnya perilaku agresif yang berakar dari realitas virtual. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa kontrol dan pembinaan yang memadai, maka tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kekerasan konten digital dapat menjadi malapetaka bagi masa depan manusia, baik secara psikologis, sosial, moral dan juga iman.
Pendahuluan ini menjadi titik awal untuk menggali lebih dalam bagaimana kekerasan dalam konten digital terbentuk, menyebar, berdampak, dan yang terpenting, bagaimana kita bersama dapat menanggapinya secara kritis dan solutif demi menyelamatkan masa depan generasi digital.
Apa itu Kekerasan?
Kata kekerasan (Inggris: Violence) berasal dari Bahasa Latin: Violentus yang berasal dari kata “Vi” atau “Vis” yang berarti “kekuasaan” atau “berkuasa”. Hal ini merupakan prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi. Semua tindakan kesewenang-wenangan, baik yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan martabat seseorang atau sekelompok orang dapat dimasukkan dalam rumusan kekerasan ini (Thomas Santoso).
Dalam Perjanjian Baru ada beberapa istilah yang dipakai untuk menunjuk pada pengertian kekerasan. Istilah-istilah itu adalah “apotomia” yang berarti “memotong” (lih. Roma 11:22). Dalam dunia Yunani, kata “apotomia” biasa dipakai untuk menunjuk pada “penghakiman Allah yang keras” atau “kekejaman oleh manusia”. Kata lain yang juga dipakai untuk menunjuk kekerasan adalah kata “analiskow” yang berarti “membinasakan” (lih. Galatia 5:15). Kata ini biasanya dipakai untuk menggambarkan perkelahian antarbinatang buas yang dengan sangat kasar saling membinasakan satu dengan yang lain. Paulus memakai kata ini untuk menyindir sikap yang bebas dan buas dari orang-orang Galatia yang menyiksa orang Yahudi.
Istilah kekerasan, menurut Injil Markus adalah “apolloumi” yang berarti “membinasakan” (lih. Markus 11:18), hal ini berhubungan dengan para imam kepala dan ahli Taurat yang bertanggung jawab atas aturan-aturan ibadah Bait Suci dan memelihara tradisi Yahudi, berusaha untuk membinasakan Yesus, sebab mereka takut kepada Yesus dengan melihat seluruh orang banyak yang takjub dengan pengajaran-pengajaran-Nya. Kata yang sama dipakai dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur (lih. Markus 12:1-12) yang menggambarkan tindakan tuan kebun anggur yang membinasakan para penggarap yang tidak bertanggung jawab itu (Samuel Hakh).
Etienne G. Krug yang mengutip World Health Organization (WHO) mendeskripsikan kekerasan sebagai “the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation”, (Etiene G. Krugh). Surip Stanasius mengatakan bahwa asal mula kekerasan karena adanya keinginan mimesis, yakni keinginan seseorang yang menginginkan apa yang diinginkan orang lain. Keinginan itu sedemikian membelenggu sehingga memunculkan persaingan dan ketika persaingan itu memuncak, lahirlah kekerasan sampai pada pembunuhan. Keinginan yang disertai hawa nafsu dan keserakahan melahirkan kekerasan.
Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kekerasan terjadi karena manusia memiliki hasrat kebencian, ambisi, ketamakan/kikir, kecemburuan, iri hati, kesombongan, ambisius, nafsu serakah, tindakan membalas dendam, dan seterusnya. Manusia juga mempunyai keinginan apa yang dimiliki oleh orang lain atau diinginkan oleh orang lain, diinginkan untuk dimilikinya juga, sehingga menimbulkan persaingan dan melahirkan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan yang melukai, membunuh, merusak, dan menghancurkan. Kekerasan berhubungan dengan tindakan agresi atau penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang dianggap sebagai tujuan dari kekuasaan dan kewenangannya. Kekerasan ini juga berdampak dalam penyalahgunaan digitalisasi sebagai ruang informasi dan komunikasi publik, sehingga menjadi kekerasan konten digital yang membawa dampak negatif.
Mengapa dan Dampak Kekerasan Konteks Konten Digital?
Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan serius, salah satunya adalah menyebarnya kekerasan dalam konten digital. Konten yang mengandung unsur kekerasan baik secara visual, verbal, maupun simbolik menjadi konsumsi rutin masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja.
Kekerasan digital tidak hanya mencerminkan tindakan brutal secara eksplisit, melainkan juga menyiratkan bentuk-bentuk kekerasan yang lebih halus melalui simbol, narasi, dan representasi media. Hal ini menjadi ancaman serius karena berpotensi mengubah cara pandang masyarakat terhadap kekerasan itu sendiri, menjadikannya sesuatu yang “normal” dan bahkan menghibur.
Dalam memahami dinamika kekerasan dalam dunia digital, penting untuk tidak hanya memperhatikan kekerasan fisik atau verbal yang eksplisit, tetapi juga bentuk kekerasan yang lebih halus dan tersembunyi, yaitu kekerasan simbolik dan representasional. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu (1991), yang menyatakan bahwa kekerasan simbolik merupakan bentuk dominasi yang dilakukan melalui simbol, bahasa, dan representasi sosial, yang diterima secara tidak sadar oleh pihak yang didominasi sebagai sesuatu yang wajar
atau alami.
Kekerasan simbolik dan representasional tersebar melalui algoritma, konten viral, dan budaya populer. Pengguna tidak selalu sadar bahwa mereka sedang terpapar ide-ide yang bisa membentuk cara pandang, memperkuat diskriminasi, atau mematikan empati. Kekerasan simbolik bekerja lewat kekuasaan yang tak terlihat, dan kekerasan representasional terjadi lewat visualisasi atau narasi yang membentuk persepsi tidak adil. Keduanya menormalisasiketimpangan dan dapat sangat berbahaya karena tidak selalu dikenali sebagai “kekerasan” dalam arti konvensional.
Kekerasan konten digital dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:
- Kekerasan Visual: Penyebaran video kekerasan fisik, penyiksaan, atau adegan pertumpahan darah dalam game dan film.
- Kekerasan Verbal: Ujaran kebencian, cyberbullying, komentar kasar, dan pelecehan daring.
- Kekerasan Simbolik dan Representasional: Meme yang menghina kelompok tertentu, penggambaran stereotip di media, serta normalisasi kekerasan dalam budaya digital.
Konten semacam ini tersebar luas melalui media sosial, platform video, dan forum daring yang belum sepenuhnya diawasi secara etis oleh algoritma maupun kebijakan perusahaan digital. Menurut teori cultivation oleh Gerbner dan Gross (1976), paparan media yang berulang terhadap konten kekerasan dapat menanamkan persepsi bahwa dunia nyata penuh ancaman. Akibatnya, konsumen media dapat mengalami ketakutan berlebihan (mean world syndrome) atau bahkan meniru perilaku kekerasan yang dikonsumsi secara visual. Paparan media dalam jangka panjang ini memberikan efek kultivasi terhadap persepsi realitas individu. Kekerasan dalam media digital dapat membentuk keyakinan bahwa dunia dipenuhi kekerasan, menciptakan rasa takut, atau bahkan memicu imitasi perilaku.
Karakteristik Kekerasan Konten Digital
Karakteristik kekerasan dalam konten digital merujuk pada ciri-ciri atau elemen-elemen yang menunjukkan adanya tindakan atau representasi kekerasan yang disebarluaskan melalui media digital. Kekerasan ini bisa berupa kekerasan fisik, verbal, simbolik, atau psikologis yang ditampilkan dalam berbagai format seperti teks, gambar, audio, video, atau interaksi digital (misalnya dalam game atau media sosial).
Berikut adalah beberapa karakteristik utama kekerasan dalam konten digital:
Visualisasi Kekerasan
- Menampilkan gambar atau video yang menunjukkan tindakan fisik yang brutal, seperti pemukulan, penembakan, pembunuhan, atau penyiksaan.
- Termasuk animasi atau adegan dalam gim video yang memperlihatkan adegan kekerasan secara eksplisit.
Kekerasan Verbal
- Mengandung kata-kata kasar, hinaan, ancaman, ujaran kebencian (hate speech), atau pelecehan verbal melalui teks atau suara.
- Sering terjadi dalam komentar di media sosial, obrolan daring (chat), atau forum digital.
Cyberbullying
- Bentuk kekerasan psikologis yang dilakukan secara berulang melalui internet atau perangkat digital.
- Contohnya termasuk penghinaan, pelecehan, penyebaran rumor, atau doxing (penyebaran informasi pribadi tanpa izin).
– Kekerasan Simbolik dan Ideologis
- Konten yang menyebarkan ideologi kekerasan, radikalisme, terorisme, atau supremasi kelompok tertentu.
- Dapat berbentuk simbol, narasi, meme, atau propaganda digital.
Normalisasi Kekerasan
- Kekerasan ditampilkan sebagai hal yang wajar, lucu, atau sebagai hiburan, sehingga dapat menumpulkan sensitivitas moral pengguna, terutama anak dan remaja.
- Sering muncul dalam bentuk video prank ekstrem, konten hiburan ekstrem, atau dalam game dengan misi kekerasan.
Anonimitas Pelaku
- Internet memungkinkan pelaku menyebarkan konten kekerasan tanpa identitas jelas, sehingga sulit dilacak dan dipertanggungjawabkan.
Penyebaran Cepat dan Luas
- Konten digital mudah dibagikan melalui media sosial, pesan instan, atau platform streaming, yang menyebabkan penyebaran kekerasan secara viral.
Kekerasan Seksual Digital
- Termasuk revenge porn, penyebaran konten seksual tanpa persetujuan, atau eksploitasi seksual berbasis digital.
- Seringkali dikemas dalam bentuk gambar, video, atau chatbot seksual.
– Interaktivitas kekerasan
- Pengguna tidak hanya menonton, tetapi juga terlibat secara aktif (misalnya dalam game online dengan aksi membunuh atau menyiksa musuh).
Konten Tidak Sesuai Usia
- Banyak konten kekerasan tidak diberi batasan umur, sehingga dapat diakses oleh anak-anak atau remaja yang belum mampu memilah konten secara bijak.
Kekerasan Simbolik dan Representasional
Bourdieu (1991) menyebutkan bahwa kekuasaan dapat ditransmisikan secara halus melalui simbol dan representasi. Dalam konteks digital, kekerasan yang dihadirkan secara berulang dapat menormalkan tindakan agresif sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diterima secara sosial. Kekerasan Simbolik dan Representasional adalah bentuk kekerasan yang tidak bersifat fisik langsung, melainkan terselubung dalam simbol, bahasa, citra, dan representasi yang memperkuat dominasi, merendahkan kelompok tertentu, atau membentuk kesadaran secara tidak kritis.
Kekerasan Simbolik dalam Konten Digital
Kekerasan simbolik bekerja melalui proses internalisasi nilai-nilai dominan yang memperkuat ketimpangan sosial. Dalam konteks media digital, hal ini tampak dalam cara algoritma dan representasi media mengulang dan meneguhkan stereotip, bias, dan ketidaksetaraan. Sebagai contoh, konten-konten yang menampilkan kelompok tertentu secara konsisten sebagai pelaku kekerasan atau objek ejekan menciptakan persepsi publik yang bias, dan secara tidak langsung memperkuat marginalisasi kelompok tersebut.
Kekerasan simbolik adalah kekuasaan yang disamarkan sebagai hal yang wajar atau alami. Kekuasaan ini dilakukan melalui simbol, seperti bahasa, norma, gaya bicara, dan representasi budaya yang memperkuat ketimpangan sosial tanpa disadari oleh pihak yang didominasi. Bourdieu (1991) menjelaskan bahwa kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang dilakukan secara tidak langsung melalui simbol, bahasa, dan representasi budaya, yang diterima secara tidak sadar oleh pihak yang didominasi. Dalam konteks digital, kekerasan ini hadir dalam bentuk stereotip media, ujaran kebencian, atau citra visual yang memperkuat dominasi dan ketimpangan sosial. Kekerasan simbolik adalah bentuk dominasi yang dilakukan melalui pengakuan dan penerimaan oleh mereka yang didominasi, karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang didominasi.
Contoh:
- Media yang terus-menerus menggambarkan kelompok tertentu (misalnya suku, agama, atau gender) sebagai sumber kekerasan atau kriminal.
- Sistem pendidikan yang memaksakan standar ‘normal’ tertentu sambil menyingkirkan keragaman budaya lokal.
- Algoritma media sosial yang menampilkan konten kekerasan sebagai hal “menghibur” dan “lazim”.
Kekerasan Representasional dalam Konten Digital
Ini adalah bentuk kekerasan yang muncul dari cara sesuatu direpresentasikan (ditampilkan) dalam media atau budaya populer yang:
- Merendahkan martabat kelompok tertentu
- Memelintir realitas
- Menyebarkan stereotip atau bias
Contoh:
- Film atau game yang menggambarkan kekerasan sebagai pahlawanisme (heroic violence)
- Meme yang mengolok-olok penderitaan korban
- Iklan yang memperkuat stigma sosial terhadap warna kulit, tubuh, atau kelas sosial
Kekerasan representasional mengacu pada cara media dan platform digital merekonstruksi realitas secara tidak adil atau menyimpang, yang dapat merendahkan martabat, memelintir identitas, atau menormalkan perilaku kekerasan. Representasi kekerasan sebagai sesuatu yang lucu, menghibur, atau bahkan heroik dalam film, game, atau konten media sosial adalah contoh dari bagaimana kekerasan menjadi estetika yang diterima dan dikonsumsi secara massal tanpa kesadaran kritis.
Kekerasan representasional terjadi ketika media menyajikan realitas secara tidak adil, memelintir makna, dan menormalisasi kekerasan sebagai sesuatu yang wajar. Dalam game, film, maupun meme digital, kekerasan seringkali ditampilkan secara estetis dan menghibur, sehingga mengaburkan batas antara realitas dan fiksi, serta memperlemah sensitivitas moral pengguna (Gerbner & Gross: 1976).
Kedua bentuk kekerasan ini sangat berbahaya karena tidak disadari sebagai kekerasan, namun memiliki dampak jangka panjang dalam membentuk cara pandang, memperlemah sensitivitas moral, dan menurunkan empati sosial. Dalam konteks ini, kekerasan simbolik dan representasional menjadi fondasi ideologis yang menormalisasi kekerasan dalam ruang digital dan mengancam.
Trolling dan Cyberbulyying
Trolling dan Cyberbulying adalah dua perilaku yang seringkali disalah artikan sebagai hal yang sama padahal memiliki dampak yang sangat berbeda (Amanina Rasyid Wiyani-Unair:2025).
- Trolling
Trolling adalah perilaku online yang sengaja memprovokasi orang lain untuk memcu reaksi yang emosional. Pelaku trolling yang biasa disebut “troll”, seringkali menulis komentar atau membuat konten yang bersifat provokatif, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Mereka melakukan ini untuk mencari perhatian atau sekadar untuk bersenang-senang melihat kekacauan yang mereka timbulkan.
Trolling biasanya anonym dan sporadic, hal ini tidak ditujukan untuk merendahkan individu tertenu, tetapi lebih kepada menciptakan keributan atau konflik yang bisa melibatkan siapa saja yang ada dalam diskusi. Biasanya, dampaknya lebih ringan dan tidak bertahan lama, meskipun masih bisa menimbulkan gangguan psikologis bagi mereka yang terlibat.
Cyberbullying
Cyberbullying adalah bentuk pelecehan atau intimidasi online dan jauh lebih berbahaya dari trolling, yang dilakukan dengan tujuan untuk menyakiti individu secara emosional. Pelaku cyberbullying sering kali mengincar korban yang sudah memiliki hubungan sosial dengannya, seperti teman atau rekan kerja. Tidak seperti trolling yang lebih sporadic, cyberbullying seringkali terjadi berulang kali, dengan niat untuk merendahkan atau menyiksa korban dalam jangka panjang.
Dampak dari cyberbullying adalah korban mengalami gangguan emosional yang mendalam, termasuk kecemasan, depresi, dan dalam beberapa kasus, bahkan pikiran untuk bunih diri. Dalam cyberbullying lebih terarah, berulang, dan memiliki dampak psikologis yang jauh lebih berat dibandingkan dengan trolling.
Jenis Konten Digital yang Berdampak Negatif
Penting bagi keluarga, gereja, sekolah dan masyarakat yang di dalamnya adalah orang tua, rohaniawan, pendidik, dan masyarakat umum untuk mengenali ciri-ciri konten negative yang dapat membahayakan anak.
Konten dengan Kekerasan atau Kekejaman
Salah satu jenis konten negatif yang sering ditemukan adalah konten yang mengandung kekerasan, baik fisik maupun psikologis. Ini bisa berupa video, gambar, atau bahkan game yang mempromosikan tindakan kekerasan, seperti pembunuhan, penyiksaan, atau perilaku destruktif lainnya. Anak-anak yang terpapar konten seperti ini beresiko mengembangkan sikap agresif kurangnya empati dan perilaku kekerasan.
Konten yang Mengandung Pornografi atau Eksploitasi Seksual
Konten yang berbau pornografi atau eksploitasi seksual jelas sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Hal ini dapat memengaruhi pemahaman mereka tentang hubungan seksual, merusak pandangan mereka terhadap tubuh dan perasaan, serta meningkatkan potensi pelecehan seksual. Konten semacam ini harus diawasi dengan ketat untuk menghindari dampak buruk jangka panjang pada kesehatan mental dan emosional anak.
Konten yang Mengajarkan Perilaku Beresiko
Konten yang mengajak anak untuk melakukan perilaku beresiko, seperti merokok, mengonsumsi alkohol, atau terlibat dalam kegiatan illegal, juga termasuk dalam kategori konten negatif. Anak-anak yang terpapar konten semacam ini bisa terpengaruh untuk meniru perilaku tersebut tanpa memahami konsekuensi yang mungkin terjadi.
Konten yang Mengandung Kebencian atau Intoleransi
Konten yang mempromosikan kebencian, diskriminasi, atau intoleransi terhadap kelompok tertentu juga sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Diskusi yang berfokus pada perbedaan ras, agama, atau status sosial dengan nada penuh kebencian dapat menanamkan sikap negatif dan merusak kemampuan anak untuk belajar menghargai perbedaan.
Konten yang Mendorong Perilaku Isolasi atau Depresi
Konten yang memperkenalkan anak pada ide-ide negative tentang diri mereka sendiri atau dunia di sekitar mereka bisa memengaruhi kesehatan mental anak. Ini termasuk konten yang mengajarkan perasaan putus asa, kesepian, atau meremehkan diri sendiri. anak-anak yang terpapar konten ini bisa merasa lebih terisolasi, mengalami kecemasan, dan dalam beberapa kasus, bisa terjerumus dalam depresi.
Konten yang Tidak Sesuai Usia
Konten yang tidak sesuai dengan usia atau perkembangan mental anak, juga perlu diperhatikan. Banyak game, film, atau video yang meskipun tidak mengandung unsur kekerasan atau pornografi, tetap tidak cocok untuk anak karena materi atau tema yang terlalu kompleks berbahaya, atau tidak realistis. Ini bisa membingungkan anak dan mengganggu pembentukan pola pikir yang sehat.
Dampak Kekerasan Konten Digital
Kekerasan konten digital memiliki dampak serius pada kesehatan mental dan kesejahteraan pengguna, terutama anak-anak dan remaja. Dampak ini bisa mencakup depresi, kecemasan, isolasi sosial, penurunan kepercayaan diri, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Selain itu, kekerasan online juga dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi pada remaja.
Berbagai dampak yang serius, adalah:
- Gangguan kesehatan mental
Kekerasan online, seperti pelecehan atau ancaman melalui pesan pribadi, dapat menyembabkan stres, depresi, dan kecemasan.
- Isolasi sosial
Korban kekerasan konten digital mungkin merasa takut untuk berinteraksi secara online atau offline, yang dapat menyebabkan isolasi sosial.
- Gangguan kepercayaan diri
Pelecehan dan kekerasan konten digital dapat merusak rasa percaya diri korban, sehingga mereka menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental lainnya.
- Gangguan kesejahteraan reproduksi
Kekerasan gender berbasis online dapat berdampak pada kesehatan reproduksi remaja.
- Penurunan prestasi akademis
Anak-anak yang mengalami kekerasan konten digital mungkin mengalami kesulitan berkonsentrasi di sekolah dan mengalami penurunan prestasi akademik.
- Pikiran bunuh diri
Dalam kasus yang ekstrem, dampak kekerasan konten digital bisa sangat parah hingga menyebabkan korban memiliki keinginan untuk bunuh diri.
Dampak Psikososial dan Kultural
Paparan kekerasan digital secara terus-menerus memiliki dampak serius, antara lain:
- Penurunan empati sosial dan desensitisasi terhadap kekerasan (Huesmann, 2007).
- Peningkatan risiko gangguan mental seperti kecemasan, trauma, dan stres pada anak-anak dan remaja.
- Perubahan nilai budaya dan moral, di mana kekerasan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang salah, melainkan sebagai hiburan atau ekspresi bebas.
Upaya Tindakan Preventif dan Kuratif Kekerasan Konten Digital
Untuk menghadapi kekerasan dalam konten digital, diperlukan dua pendekatan utama, yakni tindakan preventif dan tindakan kuratif, atau tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan konten digital.
Upaya Preventif (Pencegahan)
Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kekerasan digital sebelum terjadi atau sebelum adanya kejadian. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan edukatif, regulatif, dan teknologi. Adapun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan kekerasan konten digital, adalah:
a. Edukasi dan Literasi Digital
- Meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja tentang bahaya kekerasan digital.
- Menanamkan nilai-nilai etika digital dan empati dalam berkomunikasi online.
- Mengadakan pelatihan bagi orang tua dan guru tentang pendampingan penggunaan media digital.
b. Penguatan Regulasi
- Menerapkan dan menegakkan hukum yang melarang penyebaran konten kekerasan digital (misalnya UU ITE di Indonesia).
- Mendorong platform digital untuk membuat kebijakan komunitas yang tegas terhadap kekerasan.
c. Penggunaan Teknologi Keamanan Digital
- Memasang filter konten, aplikasi kontrol orang tua (parental control), dan perangkat lunak pendeteksi kekerasan (AI-based moderation tools)
- Mengembangkan alogaritma untuk mendeteksi dan memblokir konten yang mengandung kekerasan secara otomatis.
d. Peran Keluarga dan Institusi Pendidikan
- Keluarga menjadi pengawas pertama dalam penggunaan gadget oleh anak-anak
- Sekolah memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum pembelajaran.
e. Bijak Berinteraksi di Dunia Maya
– Sebelum berkomentar atau membagikan informasi, penting untuk berpikir dulu. Hindari terlibat dalam provokasi atau diskusi yang tidak sehat. Menghindari konflik di dunia maya adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari serangan negatif.
f. Gunakan Fitur Privasi dan Laporkan Perilaku Negatif
– Platform media sosial memiliki pengaturan privasi yang memungkinkan kita untuk membatasi siapa yang dapat melihat konten atau berinteraksi dengan kita. Manfaatkan pengaturan ini untuk menjaga keamanan pribadi. Jika mengalami trolling dan cyberbullying segera laporkan tindakan tersebut.
Tindakan Kuratif (Penanganan) Kekerasan Konten Digital
Tujuannya adalah untuk menangani dan memulihkan dampak yang terjadi setelah seseorang terpapar atau menjadi korban kekerasan digital.
- Pelaporan dan penegakan hukum
- Mendorong korban untuk melapor ke pihak berwenang seperti polisi siber (cyber police) atau Kominfo.
- Menyediakan kanal pelaporan secpat di platform digital.
- Pendampingan psikologis
- Memberikan layanan konseling bagi korban kekerasan digital, terutama anak dan remaja.
- Membantu pemulihan trauma melalui terapi yang sesuai.
- Pemulihan reputasi digital
- Menghapus atau menurunkan konten kekerasan dan internet (take down content).
- Mengedukasi korban dan keluarga tentang cara menjaga privasi digital.
- Rehabilitasi pelaku
- Memberikan edukasi dan rehabilitasi kepada pelaku kekerasan digital, terutama jika pelaku masih usia anak/remaja.
- Mengupayakan pemulihan hubungan sosial melalui pendekatan restorative.
- Mencari dukungan
- Jika merasa tertekan atau menjadi korban perilaku online yang merugikan, penting untuk mencari dukungan dari teman-teman, keluarga, atau bahkan konselor profesional. Mereka bisa membantu mengatasi dampak emosional yang ditimbulkan.
Peran Pendidikan Agama Kristen
Kekerasan konten digital adalah wajah baru kekerasan yang tak terlihat. Kekerasan digital tidak selalu berbentuk fisik, namun dampaknya dapat menghancurkan mental dan spiritual seseorang. Dalam konteks inilah, Pendidikan Agama Kristen (PAK) tidak bisa tinggal diam. Sebagai sarana pembentukan karakter dan iman peserta didik, PAK memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjadi benteng terhadap derasnya arus kekerasan digital. Tanpa pendidikan yang menanamkan kasih, empati, dan tanggung jawab digital, generasi muda terancam kehilangan arah, kemanusiaan, dan martabatnya sebagai gambar dan rupa Allah (Imago Dei).
Pendidikan Agama Kristen memiliki akar kuat dalam ajaran Alkitab yang menekankan nilai-nilai kasih, damai sejahtera, pengendalian diri, dan penghormatan terhadap sesama. Dalam Kejadian 1:26-27, manusia ditegaskan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka, setiap bentuk kekerasan terhadap sesama, termasuk di dunia maya, adalah bentuk penghinaan terhadap karya penciptaan Allah.
Yesus sendiri mengajarkan agar kita mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita (Matius 5:44), serta hidup sebagai pembawa damai (Matius 5:9). PAK harus mampu menanamkan nilai-nilai tersebut di tengah dunia digital yang keras dan penuh kebencian. Pendidikan Agama Kristen berfungsi sebagai suara kenabian yang mengingatkan, menegur, dan membentuk karakter Kristus di tengah generasi digital.
PAK memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran dan karakter peserta didik agar mampu menghadapi serta menolak kekerasan digital. Peran-peran tersebut antara lain:
Pendidikan Etika Digital Berbasis Iman
PAK perlu mengintegrasikan literasi digital dan etika Kristen dalam kurikulumnya. Nara didik diajar bukan hanya tentang bahaya kekerasan digital, tetapi bagaimana mereka harus bersikap sebagai murid Kristus di dunia maya. Nilai kasih, kebenaran, dan pengampunan harus menjadi dasar dalam setiap interaksi digital.
Pendampingan Digital
Keluarga, gereja dan sekolah dalam hal ini orang tua, pelayan gereja serta guru berperan sebagai mentor rohani yang mendampingi anak dalam menghadapi tantangan digital. Mereka bukan hanya menyampaikan materi, tetapi menjadi pendengar dan penolong dalam situasi ketika anak-anak kita mengalami perundungan atau tekanan digital.
Kritik terhadap Budaya Kekerasan
PAK harus berani menjadi suara profetik yang menyuarakan kebenaran terhadap budaya digital yang permisif terhadap kekerasan. Ini berarti menolak normalisasi konten kekerasan, tidak kompromi terhadap budaya “viral” yang merusak nilai-nilai kemanusiaan.
Mendorong Produksi Konten Digital yang membangun
PAK dapat memotivasi semua pihak untuk membuat konten digital positif yang mencerminkan nilai-nilai Kristiani, dengan manjadi terang dan garam dunia (Matius 5:13-14), termasuk di dunia digital.
PAK haruslah selalu relevan dengan konteks yang ada dengan pelaksanaan tugas untuk memperlengkapi warga gereja yang di dalamnya generasi muda, agar mampu menghadapi tantangan zaman, termasuk fenomena kekerasan konten digital, dengan nilai-nilai Kristiani yang mendalam. Pendidikan ini bertujuan membentuk karakter yang mencerminkan kasih Kristus, membangun kesadaran etis bermedia digital, serta mendorong peran aktif sebagai agen damai dan terang di tengah dunia maya yang penuh gelapnya kebencian dan kekerasan. Ketika PAK tidak lagi relevan atau diam terhadap fenomena kekerasan digital, maka generasi muda akan:
- Terbiasa dengan kekerasan.
- Kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah.
- Tidak lagi memiliki empati terhadap penderitaan sesama.
- Bahkan menjadi pelaku kekerasan digital.
Malapetaka ini bukan hanya menyangkut masa depan individu, tetapi masa depan gereja dan bangsa. Tanpa pendidikan iman yang kontekstual dan relevan, PAK hanya akan menjadi pelajaran hafalan tanpa transformasi.
Penutup
Kekerasan dalam konten digital bukan sekedar isu marginal, melainkan merupakan fenomena serius yang mengancam struktur psikologis dan sosial masyarakat. Kekerasan dalam konten digital telah menjadi alat normalisasi kekerasan dalam budaya populer. Jika tidak direspon dengan pendekatan literasi digital, regulasi, pendidikan karakter yang memadai, serta peran Pendidikan Agama Kristen, dapat menjadi malapetaka bagi masa depan generasi muda, merusak tatanan nilai, empati, dan integritas kemanusiaan.
Kekerasan konten digital harus direspons secara serius, karena ini menjadi ancaman serius yang berpotensi merusak masa depan secara psikis dan moral, melalui pendidikan, regulasi, dan pendekatan lintas sektor, karena konten kekerasan digital dapat menjadi malapetaka kultural dan sosial yang sulit untuk dibendung. Upaya pencegahan dan penanganan atau tindakan preventif dan kuratif secara sistematis dan kolaboratif dalam membangun budaya digital yang sehat, manusiawi, dan etis haruslah dapat ditanggapi dan dilakukan, agar kekerasan konten digital segera dicegah dan mendapat penanganannya.
Pendidikan Agama Kristen harus hadir secara aktif, kreatif, dan kritis menghadapi tantangan kekerasan konten digital. PAK bukan hanya berbicara tentang keselamatan rohani, tetapi juga tentang martabat manusia, etika hidup, dan tanggung jawab sosial di era digital. PAK harus mengintegrasikan literasi digital dalam kurikulum baik di sekolah dan gereja, serta menjadi pengajaran mulai dari keluarga, gereja dan sekolah dan menjadi tanggung jawab semua pihak. Sekolah dan gereja perlu mengadakan pelatihan bagi guru dan orang tua tentang pengawasan dan pendampingan digital. Pendidikan Agama Kristen perlu menjadi penggerak budaya digital yang berkeadilan, damai, dan membangun. Dengan demikian, PAK menjadi instrumen ilahi untuk menyelamatkan generasi digital dari malapetaka kekerasan konten digital, dan membentuk mereka menjadi pribadi yang memuliakan Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam dunia digital.
Daftar Pustaka
Bourdieu, P. (1991). Language and symbolic power. Harvard University Press.
Etienne G.Krug. (2002). World Report on Violence and Health. World Health Organization.
Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Living with television: The violence profile. Journal of Communication, 26(2), 172–199. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1976.tb01397.x
Huesmann, L. R. (2007). The impact of electronic media violence: Scientific theory and research. Journal of Adolescent Health, 41(6 Suppl), S6–S13. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2007.09.005
Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2007). Gradations in digital inclusion: Children, young people and the digital divide. New Media & Society, 9(4), 671–696. https://doi.org/10.1177/1461444807080335
Nasrullah, R. (2021). Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi (3rd ed.). Kencana.
Samuel B. Hakh. (2013) “Kekerasan Mengatasnamakan Agama: Suatu Tinjauan Etis-Alkitabiah dari Sudut Perjanjian Baru” Jurnal Teologi Sola Experientia.
Surip Stanisius. Mematahkan Siklus Kekerasan. Kanisius.
UNESCO. (2019). Media and information literacy curriculum for teachers. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189756
Thomas Santoso, Teori-teori Kekerasan. Ghalia Indonesia.[1]

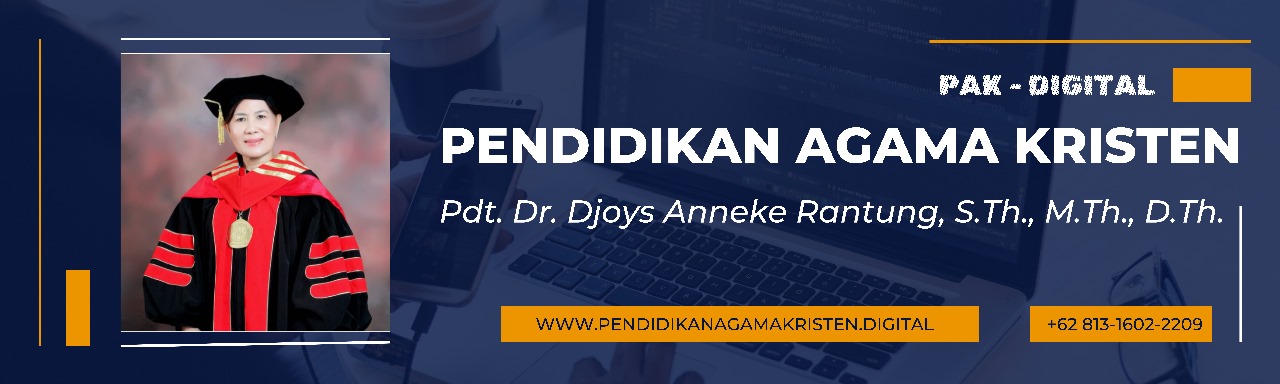

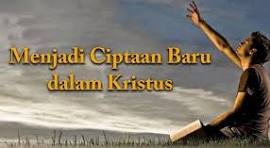

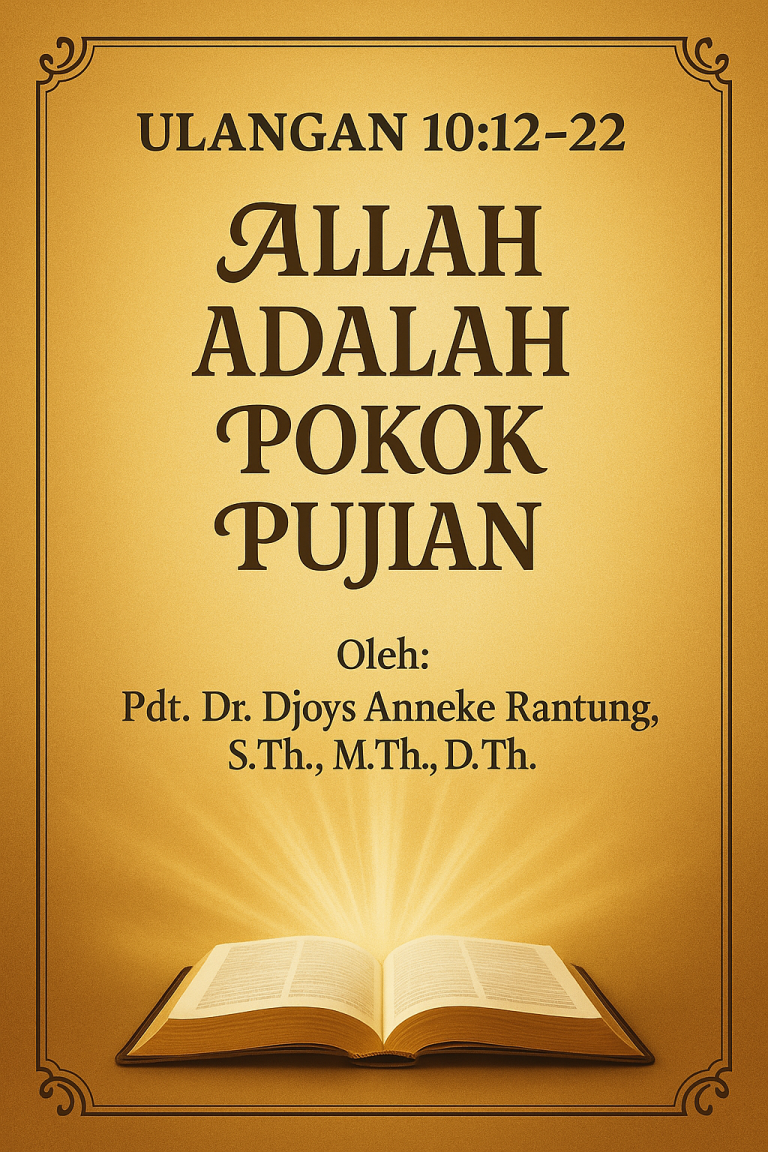
Your point of view caught my eye and was very interesting. Thanks. I have a question for you.
with pleasure
Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!